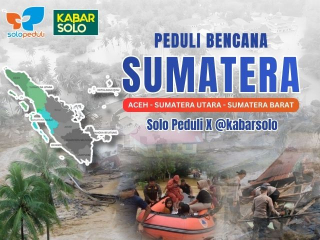Integrasi bangsa Indonesia telah melewati proses historis yang panjang. Sebgai proses peyatuan sebuah bangsa, integrasi mulai berlangsung sejak awal abad Masehi, mengalami kemajuan di abad 16 sampai abad ke-19, diteruskan pada abad ke-20 melalui gerakan kebangsaan, dan puncaknya adalah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.
Secara etimologis, integrasi berasal dari kata Latin integrare, kata benda integrasi dan kata sifat integer yang dapat dimaknai membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam konteks nasional, integrasi merupakan perasaan kesatuan bangsa yang dibangun karena adanya berbagai persamaan historis yang melahirkan kesadaran sebagai sebuah bangsa yang memiliki cita-cita bersama menuju negara merdeka.
Islam dan Integrasi Bangsa
Integrasi bangsa Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan sejak proses islamisasi. Islam masuk dan berkembang di Nusantara mengabarkan kebersamaan, toleransi, dan persamaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai agama yang berkembang di Nusantara, Islam mampu mengatasi perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa dan menjadi identitas yang melampaui batas kewilayahan, sentimen etnis, adat istiadat, dan tradisi lokal lainnya.
Ulama memiliki peran penting dalam mewujudkan integrasi bangsa. Para cendekiawan berperan sebagai guru agama sekaligus agen pembangunan umat. Sebagai contoh, Datuk Patimang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Ri Bandang, ulama Minangkabau berhasil mengislamkan masyarakat Sulawesi, begitu juha Syekh Umar Al-Bantany, ulama Jawa berperan dalam mengislamkan masyarakat di Bima. Demikian pula, ulama dari Giri, Jawa TImur telah mengislamkan masyarakat di Ternate dan Tidore (De Graaf, 2001).
Islam menjadi elemen pemersatu dan mendorong pemakaian bahasa Melayu berkembang merata di kepulauan Nusantara. Bahasa ini, sebelum kedatangan Islam hanya digunakan terbatas di kalangan masyarakat Sumatra dan semenanjung Tanah Melayu. Bahasa Melayu diadopsi sebagai lingua franca oleh para penyiar Islam, ulama, dan pedagang. Bahasa ini dalam perkembangannya, menjadi bahasa perantara dan pergaulan di seluruh Nusantara.
Di era perdagangan antarpulau, laut menjadi jalan penghubung sekaligus pemersatu penduduk di kepulauan Nusantara. Para pedagang dari Jawa yang berdagang ke Palembang dan sebaliknya mendorong terciptanya integrasi antara Sumatera dan Jawa. Para pedagang di Banjarmasin berdagang ke Makassar, atau sebaliknya ikut membantu integrasi antara masyarakat di Kalimantan dengan masyarakat Sulawesi.
Bahasa Melayu sebagai bahasa dengan karakter egalitarian dan sifat kosmopolitnya menjadi bahasa kebudayaan Islam di Nusantara dan bahkan Asia Tenggara. Selanjutnya, bahasa ini diintegrasikan dalam konteks politik sebagai bahasa nasional dengan sebutan "bahasa Indonesia" (Muljana, 1964). Dengan demikian, bahasa Melayu memainkan peran sangat besar dalam membawa masuk pengaruh Islam ke dalam budaya politik modern Indonesia.
Dalam perspektif historis, Islam telah memberi suntikan motivasi umatnya untuk berkorban dalam mengusir penjajah, Islam menjelma menjadi kekuatan vital dalam merebut kemerdekaan. Pada awal abad ke-20 gerakan ini hadir dengan semangat pembaharuan keagamaan dan anti penjajahan. Mereka berjuang membangun kesadaran beragama sekaligus berbangsa. Oleh karena itu, Islam pada masa ini fokus pada upaya mengangkat derajat rakyat Indonesia dan mengusir penjajah dari Tanah Air.
Secara politis, Islam menempati posisi yang sangat fundamental di dalam Pancasila sebagai dasar negara, di mana para pendiri bangsa telah menunjukkan kearifan kebangsaan dengan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila utama. Dalam kehidupan bernegara, Islam menjadi sumber kekuatan spiritual, moral, dan etika. Nilai-nilai spiritual Islam menjadi pendorong bagi umatnya untuk mewujudkan harmoni sosial.
Dalam perjalanan sejarahnya, proses integrasi nasional telah menempatkan Islam sebagai elemen penting. Akan tetapi, saat ini isu yang muncul justru Islam distigmatisasi dapat menjadi ancaman integrasi bangsa. Isu yang menyeruak di antaranya persoalan perbenturan agama dan negara, radikalisme dan ekstrimisme di tengah masyarakat. Kontestasi politik acap kali muncul dalam bentuk polarisasi yang ekstrem antara politik agama dan non-agama.
Negara dan agama Islam adalah dua entitas yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki hubungan simbiotis, saling membutuhkan dan mengisi. Di masa kini, Islam sudah saatnya tampil sebagai realitas baru bagi landasan pembangunan bangsa. Islam dapat ditempatkan sebagai fondasi, sedangkan negara adalah penjaganya. Dengan demikian, Islam sebagai faktor pemersatu dan sumber moralitas kehidupan bangsa dapat terus dijaga.
Penulis: Dr. Mukhammad Shokheh, M.A - Sejarawan
Sumber: Majalah Hadila Edisi 182
Foto: Lukisan karya Dullah